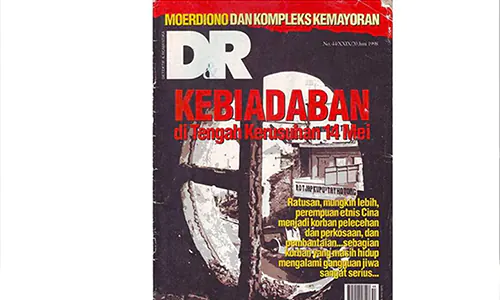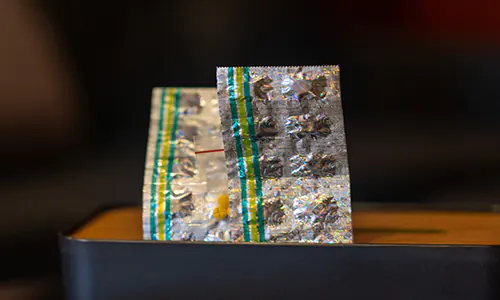PARBOABOA, Jakarta - Intimidasi dan kekerasan terhadap jurnalis lazim terjadi di Indonesia selama beberapa tahun terakhir.
Divisi Advokasi Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia melaporkan sebanyak 84 kasus kekerasan terhadap jurnalis sepanjang tahun 2020.
Angka ini mengalami peningkatan signifikan dibandingkan dengan tahun 2019 yang hanya mencatat 53 kasus.
Meski demikian, laporan tahun 2020 mencatat rekor tertinggi sejak AJI mulai memantau kasus kekerasan terhadap jurnalis selama lebih dari 10 tahun lalu.
Lebih lanjut, TIFA Foundation dan Populix dalam survei bersama 536 responden mengungkapkan bahwa 45% jurnalis pernah mengalami kekerasan saat bertugas.
Dari segi bentuk kekerasan, jenis yang paling umum adalah pelarangan peliputan, di mana 46% responden atau 112 jurnalis melaporkan adanya kejadian tersebut.
Di posisi kedua, 41% responden mengaku mengalami pelarangan pemberitaan. Urutan ketiga diisi teror dan intimidasi yang dialami 39% jurnalis responden.
Sementara di urutan keempat, sekitar 31% jurnalis mengaku pernah diminta untuk menghapus hasil liputan mereka karena dituduh menyerang pihak-pihak tertentu.
Direktur Eksekutif Yayasan TIFA, Oslan Purba, menyoroti bahwa keselamatan jurnalis di Indonesia masih jauh dari kata aman.
Menurutnya, ancaman terhadap jurnalis mayoritas berasal dari aparat negara dan organisasi masyarakat (ormas).
Secara rinci, responden jurnalis mengidentifikasi potensi ancaman terbesar dinilai berasal dari ormas dengan persentase 29%, diikuti oleh negara melalui aparat kepolisian sebesar 26%.
Selanjutnya, pejabat pemerintah menjadi sumber ancaman bagi 22% jurnalis, sementara aktor politik menyumbang 14% ancaman.
Terbaru, Pemimpin Redaksi (Pemred) Floresa, Herry Kabut ditangkap aparat pada Rabu (02/10/2024) siang saat meliput aksi unjuk rasa penolakan proyek Geothermal di Poco Leok, Kabupaten Manggarai.
Hingga pukul 15.00 Wita, Herry masih berada di dalam mobil aparat bersama beberapa warga. Floresa berupaya memverifikasi jumlah pasti warga yang ditangkap.
Kehadiran Herry di Poco Leok semata bertujuan untuk meliput aksi protes warga yang sejak sehari sebelumnya terlibat konfrontasi dengan pemerintah dan PT PLN.
Menurut salah seorang warga, Herry tiba-tiba ditarik oleh aparat begitu tiba di lokasi. Ia kemudian “dipukul saat hendak masuk ke dalam mobil.”
"Sejumlah warga mencoba merekam video dan foto saat penangkapan, namun dihalangi aparat," tulis Floresa dalam keterangan yang diterima PARBOBOA, Rabu (02/10/2024).
Hingga kini, pihak Floresa belum berhasil berkomunikasi dengan Herry. Dugaan kuat, Herry ditahan aparat lantaran getol menyoroti kritikan terhadap pembangunan Geothermal.
Pelanggaran HAM dan Demokrasi
Intimidasi terhadap jurnalis tergolong sebagai salah satu bentuk pelanggaran terhadap HAM, khususnya terkait kebebasan berekspresi dan berpendapat.
Dalam perspektif HAM, wartawan dan profesi lain yang berhubungan dengan pemberitaan mengenai isu kemanusiaan dapat dikategorikan sebagai pembela HAM.
Hal ini karena tugas mereka mencakup upaya untuk menyebarkan informasi, mengungkap pelanggaran, dan membela hak-hak individu atau kelompok rentan.
Sebagai penjaga transparansi dan akuntabilitas, wartawan turut berkontribusi dalam memperjuangkan HAM. Mereka menjadi bagian integral dari upaya perlindungan HAM di tengah masyarakat.
Kebebasan berpendapat dan berekspresi merupakan fondasi bagi terwujudnya kebebasan pers, sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Universal Declaration of Human Rights.
Di Indonesia, intimidasi terhadap wartawan sesungguhnya bertentangan dengan prinsip demokrasi yang mengakomodasi kebebasan menyatakan pendapat dan hak mengawasi pemerintahan.
Founder dan Direktur The Indonesian Agora Research Center dan Ranaka Institute, Fredi Jehalut menyebut, intimidasi terhadap Pemred Floresa sebagai tindakan yang tidak bisa dibenarkan.
"Selain menyalahi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Kebebasan Pers, tindakan tersebut juga melanggar hak atas kebebasan berpendapat yang diatur dalam Pasal 28E Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945," ungkapnya kepada PARBOABOA, Rabu (02/10/2024).
Lebih dari itu, tindakan intimidasi dan kekerasan yang dilakukan aparat terhadap warga Poco Leok dan jurnalis merupakan bentuk pelanggaran "hak-hak asasi manusia" melalui penindakan (by commission).
"Oleh karena itu, pelakunya harus diusut dan ditindak tegas," terang alumnus filsafat di IFTK Ledalero itu.
Pendapat Ferdi hendak menegaskan kewajiban negara dalam menjamin kebebasan mengemukakan pikiran dan pendapat, sesuai amanat Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945.
Beleid ini menyebutkan bahwa hukum tidak boleh melarang kebebasan berekspresi seorang jurnalis, selama tidak ditujukan untuk penghinaan, kebencian, atau pencemaran nama baik.
Menurut Abdurrakhman Alhakim (2022) dalam riset berjudul Urgensi Perlindungan Hukum terhadap Jurnalis dari Risiko Kriminalisasi UU Informasi dan Transaksi Elektronik di Indonesia, ada beberapa prasyarat suatu negara dikatakan menjamin kebebasan pers.
"Di antaranya, jurnalis tidak diwajibkan meminta izin penerbitan kepada pemerintah dan pemerintah tidak berwenang menyensor informasi yang akan diterbitkan," tulis Alhakim.
Ia juga menambahkan bahwa pemerintah secara hukum tidak boleh melarang penerbitan pers dalam jangka waktu tertentu.
Sebab, intimidasi dan kekerasan terhadap jurnalis justru berdampak mengikis pemikiran kritis dan keberanian dalam menghadapi kekuasaan.
"Fenomena ini bertentangan dengan pernyataan pemerintah mengenai jaminan kebebasan pers, seperti yang diatur dalam UU Pers," lanjut Alhakim.
Meskipun undang-undang pers menetapkan hukuman bagi siapa saja yang menghalangi kebebasan pers, kenyataannya masih 'jauh panggang dari api'.
Intimidasi terhadap Pemred Floresa menunjukkan secara jelas sikap negara yang abai terhadap kebebasan pers, selebihnya hak-hak dasar jurnalis yang harus dilindungi.
Apa yang terjadi di Poco Leok?
Proyek Geothermal Poco Leok merupakan perluasan dari PLTP Ulumbu yang sudah beroperasi lebih dari satu dekade dan berjarak sekitar tiga kilometer di sebelah barat Poco Leok, Kabupaten Manggarai.
Proyek ini merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN) di Pulau Flores dan tercantum dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik PT PLN 2021-2030.
Desain tapak PLTP Ulumbu Unit 5-6 di Poco Leok, menurut sosialisasi pemerintah, bertujuan meningkatkan kapasitas listrik dari 7,5 MW menjadi 40 MW.
Proyek ini dibagi ke dalam beberapa zona, yaitu Wellpad D yang terletak di Lingko Tanggong dan Wellpad E yang mencakup Kampung Cako, Leda, serta Lelak di Desa Lungar.
Meskipun demikian, warga Poco Leok yang hidup dan menempati 14 kampung adat di Kecamatan Satar Mese, terus menolak proyek tersebut karena merasakan dampak ekologis yang merugikan.
Sejumlah kejadian seperti tanah longsor, banjir, dan menurunnya tanah acap kali dialami warga yang tinggal di Poco Leok.
Selain itu, pembangunan proyek Geothermal untuk meningkatkan ketersediaan energi listrik disinyalir bukan sebagai kebutuhan prioritas warga.
Proyek ini justru berlangsung di tengah situasi surplus elektrifikasi, baik secara nasional maupun lokal.
Keberlanjutan proyek Geothermal di Poco Leok lantas menuai perdebatan, terutama terkait dengan dampaknya terhadap masyarakat setempat dan lingkungan.
"Soal polemik Geothermal Poco Leok, problemnya menurut saya terletak pada buruknya komunikasi publik dan pendekatan yang dilakukan pemerintah," tegas Ferdi Jehalut.
Pemerintah, ungkapnya, tidak menjelaskan secara proporsional kepada masyarakat soal dampak positif dan negatif proyek Geothermal.
Selain itu, komitmen mereka terhadap nasib warga di sekitar area proyek juga tampak lemah.
Oleh karena itu, Fredi mendesak agar semua kebijakan publik yang diambil mestinya mengedepankan prinsip partisipasi publik yang bermakna.
"Artinya, suara masyarakat itu perlu didengarkan. Jangan memaksakan [kelanjutan] proyek yang sudah ditolak oleh masyarakat."
Menurutnya, dalam situasi kritis dan krisis, pemerintah secara terpaksa hanya mengandalkan pendekatan teknokratis. Namun, dalam situasi normal, pendekatan teknokratis saja tidak cukup.
"Harus ada partisipasi publik yang bermakna, sehingga kebijakan tersebut tidak menimbulkan resistensi yang masif," tutup Ferdi.
Editor: Defri Ngo