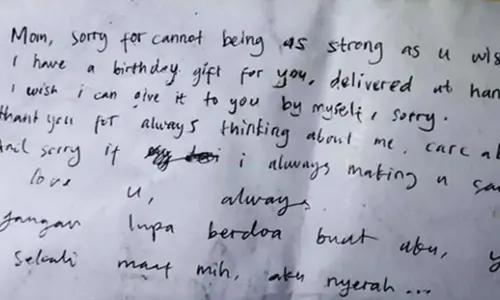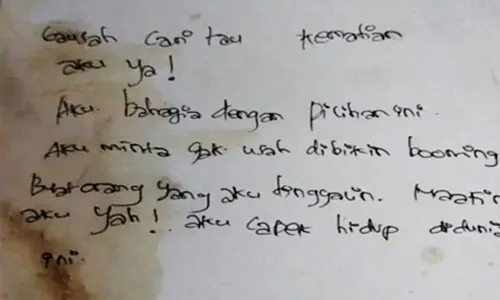Tulisan-3 Merayakan Seabad Sastrawan Utama Sitor Situmorang
PARBOABOA - Di Medan Sitor Situmorang tak jenak. Tidak heran sebab jagat pergaulannya sudah menasional. Ke Jakarta ia kembali, tak lama berselang. Anak-istrinya tak ikut sebab mantan jurnalis Waspada sudah tak punya pekerjaan.
Setelah beberapa saat menganggur ia akhirnya mendapatkan pekerjaan dari Usmar Ismail sebagai penerjemah naskah drama. Berada di lingkungan tokoh perfilman itu aksesnya pun terbuka ke Lingkaran Gelanggang yang menerbitkan majalah Siasat. Lewat rubrik Gelanggang di terbitan yang diasuh Soedjatmoko, Amir Pasaribu, Basuki Resobowo, Asrul Sani, dan Rivai Apin inilah puisi-puisinya mulai dikenal publik.
Sebagai penyair yang sudah punya nama, pada 1950 ia beroleh beasiswa lembaga kerja sama Belanda-Indonesia, Sticusa, untuk tinggal di negeri kincir angin (Amsterdam) setahun.
Setelah program Sticusa berakhir ia pindah ke Paris untuk menjadi pegawai Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI). Selama di Eropa ia belajar banyak hal termasuk filsafat. Eksistensialisme yang mulai mekar saat itu ia geluti. Buah pena Soren Kierkegaard, Friedrich Nietzsche, Franz Kafka, Fyodor Dostoyevsky, Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, Albert Camus, Eugene Ionesco, dan yang lain pun digelutinya. Untuk seterusnya karya-karyanya nyata terpengaruh oleh bacaan tersebut. Individualisme, keterasingan, dan absurditas merupakan cirinya.
Tahun 1953 ia kembali ke Jakarta. Kumpulan puisi perdananya, Surat Kertas Hijau, terbit tahun itu juga. Karya yang merupakan terobosan ini seketika menjulangkan namanya di dunia sastra Indonesia. Di Tanah Air ia segera giat menulis esai, telaah-kritik, dan cerpen, selain puisi.
Pemuka di lapangan sastra-budaya ini berkesempatan mendalami film dan drama di Universitas California pada 1956-1957. Sepulang ke Jakarta ia malah sempat terjun lagi ke media massa yakni menjadi awak koran Berita Nasional dan Warta Dunia. Pernah juga dia bergiat sebagai pegawai jawatan Pendidikan dan Kebudayaan, dosen Akademi Teater Nasional Indonesia, anggota Dewan Perancang Nasional, dan anggota Badan Pertimbangan Ilmu Pengetahuan.
Sebagai Soekarnois tulen ia lantas menjadi Ketua Lembaga Kebudayaan Nasional (1959-1965) dan anggota MPRS (wakil karyawan seniman). Di masa giat berpolitik itu karya-karyanya—seperti halnya buah pena para penyair Lembaga Kebudayaan rakyat (Lekra)—menjadi hambar karena sarat muatan ideologis.
Membui
Soekarno ditumbangkan rezim Orde Baru. Senasib dengan orang-orang Lembaga Kebudayaan Rakyat (Lekra), Sitor yang merupakan dedengkot Lembaga Kebudayaan Nasional harus menelan pil pahit. Ia meringkuk 8 tahun (1966-1974) di bui Salemba. Selama mendekam ia tak menulis sebab ‘barang sepotong pensil pun’ diharamkan penguasa di sana.
Sekeluar dari penjara ia bertekun betul berkarya. Juga, menyempatkan diri menjelajah Pulau Jawa dan Bali. Kekuatannya sebagai sastrawan utama pulih kembali. Laksana tanggul jebol, berlimpah puisi ia hasilkan termasuk yang berbahasa Inggris dan Belanda.
Sejak 1984 ia bermukim di Belanda (Leiden dan Den Haag) dan di sana menikah dengan, Barbara Brouwer, diplomat negara itu. Sang penyair sempat menjadi dosen di Universitas Leiden. Barbara Brouwer pindah tugas ke Islamabad, Pakistan, pada 1991. Pasangan ini bermukim di sana hingga 1995.
Pada periode 2000-2005 suami-istri yang memiliki anak tunggal bernama Leonard tinggal di Jakarta. Seterusnya mereka lebih banyak berada di mancanegara.
Ihwal Sitor Situmorang, ada catatan kecil dari sahabatnya, Pramoedya Ananta Toer. Ke aku, Rin, dan Rhein yang sedang menyiapkan kitab Pram Melawan penulis tetralogi Pulau Buru pernah bercerita ihwal penyair pengembara ini. Ia mengatakan Sitor seorang lelaki berenergi besar yang selama di bui Salemba tersohor di antara para tahanan politik bukan saja karena pencapaiannya sebagai penulis tapi juga karena keperkasaannya yang menggetarkan perempuan mana pun.
Pram juga mengatakan ada satu hal yang tak ia sukai dari sobatnya itu.
“Ia meninggalkan begitu saja istri dan anak-anaknya begitu dirinya bebas dari penjara Salemba,” tutur Pram.
Pram dan Sitor berkawan sejak keduanya masih belia.
Sitor Situmorang pernah menghasilkan puisi yang maha pendek. Idenya muncul saat dia menapak ke rumah Pram di malam lebaran. Judulnya Malam Lebaran. Isinya? Cuma: Bulan di atas kuburan. Karya yang dibuatnya tahun 1955 ini kontan menjadi buah bibir sekaligus kontroversi hingga lama.
Sebait saja dan lariknya pun kelewat pendek. Sungguh tak lazim. Itu yang membuatnya ramai dipercakapkan orang. Lantas, ada yang menyoal bahwa tak ada bulan di langit pas malam lebaran. Mereka yang membela Sitor berargumen bahwa simbolisme, metafora, simile, dan majas lain yang lain adalah unsur yang tak terpisahkan dari puisi. Memang, demikian adanya.
Seperti kutulis di bagian sebelumnya, di pelbagai puisinya Sitor mengungkapkan rasa bersalahnya terhadap keluarga. Pada sisi lain ia menganggap ketakbecusannya sebagai kepala rumah tangga sebagai kutukan yang jatuh pada diri setiap kelana. ‘Perang antara kesetiaan dan pengembaraan’ memang seumur hidup dihadapinya.
Banyak Talenta
Aku kenal karya Sitor Situmorang setelah mahasiswa saja. Sebagai orang baru dan penyepi, di kampus aku acap menjambangi perpustakaan Universitas Padjajaran, di Jl. Dipati Ukur, Bandung. Di koleksi Profesor Kabullah yang agak terlantar, suatu waktu aku menemukan Surat Kertas Hijau edisi pertama (1953). Begitu menyibak isinya aku langsung terpukau.
Dia dan Aku, Surat Kertas Hijau, Berita Perjalanan, Kebun Binatang, Chatedrale de Chartres, The Tale of Two Continents, Orang Asing, Sajak, Paris-Janvier, Paris-Avril, Pont Neuf, Kepada Anakku, dan Tour Eiffel yang termaktub di buku tipis ini sungguh kusuka. Kesegaran, kebeningan, kelangsungan, dan kedalamannya sungguh terasa. Pun rentang jelajahnya. Berbeda dari karya para pujangga lama yang diajarkan sewaktu aku masih di sekolah menengah.
Seiring waktu aku mengenal karya Sitor lebih dekat. Puisinya yang lebih lengkap kunikmati lewat Bunga di Atas Batu (Si Anak Hilang) yang diedit Pamusuk Eneste. Karya yang diterbitkan PT Gramedia tahun 1989 ini berisi 347 sajak.
Belakangan (Januari 2006), hadir lagi buku puisi Sitor yang lebih tebal. Karya dari periode 1948-1979 dan 1980-2005 ini berjumlah 605 sajak yang termaktub dalam 2 buku berhalaman banyak. Pengumpul dan penyuntingnya adalah sejarawan JJ Rizal. Tak syak lagi: Sitor adalah penyair Indonesia yang paling panjang staminanya dan terbernas.
Sitor bertalenta banyak. Kemampuannya sebagai wartawan nyata dari sajian perkisahan kaya detil di biografinya. Kekuatannya sebagai cerpenis terlihat di kumpulan cerita Salju di Paris. Kepiawaiannya sebagai eseis-kritikus-cum ahli propaganda, tampak di buku Sastra Revolusioner. Kehebatannya sebagai sejarawan terbukti lewat kitab Toba Na Sae. Tentu dia juga kritikus seni rupa dan penerjemah yang berwibawa.
Sungguh beruntunglah, menurutku, Indonesia memiliki seorang Sitor Situmorang yang ulang tahun keseratusnya baru saja kita rayakan (pada 2 Oktober 2024).
Editor: Hasudungan Sirait