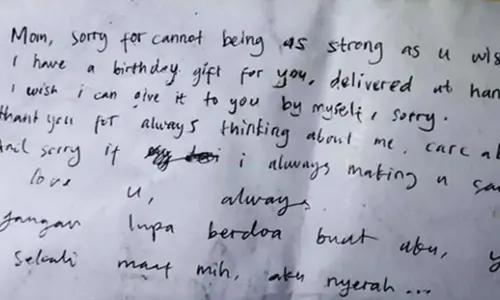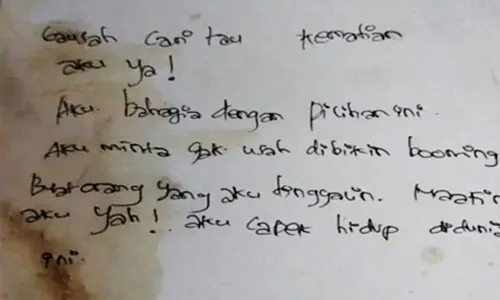PARBOABOA, Jakarta - Dalam lawatannya ke Beijing belum lama ini, Presiden Prabowo Subianto menyepakati kerjasama ekonomi maritim dengan negeri tirai bambu.
Kerjasama yang ditandatangani Prabowo dan Presiden Xi Jinping itu, fokus pada konservasi perikanan di Laut Natuna yang terletak di Kawasan perairan China Selatan.
Namun begitu, terobosan tersebut menuai kecaman dari dalam negeri mengingat klaim sepihak China terhadap laut Natuna selama ini.
Ada semacam kekhawatiran, melalui kesepakatan dua kepala negara, Indonesia mengakui begitu saja klaim China.
Apalagi isi paragraf 2 dan 9 kesepakatan menyebut, "kedua pemerintah mencapai kesepahaman tentang pengembangan wilayah maritim yang overlapping claims atau dalam situasi klaim tumpang tindih."
Pengamat Hubungan Internasional Universitas Indonesia (UI), Aristyo Rizka Darmawan dalam sebuah keterangan pada Selasa, (12/11/2024) mengatakan Indonesia sendiri sebenarnya tidak memiliki klaim yang tumpang tindih dengan China.
Indonesia sejak awal, kata dia, telah menolak klaim China di Laut China Selatan, khususnya setelah Mahkamah Arbitrase Internasional pada tahun 2016 menegaskan bahwa konsep 'nine-dash-line' atau sembilan garis putus-putus yang digunakan China untuk mempertegas wilayah klaimnya, tidak diakui dalam kerangka UNCLOS (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut).
Namun, adanya pernyataan bersama yang menyebut bahwa kedua negara "mencapai kesepahaman terkait pengembangan bersama di wilayah maritim yang saat ini berada dalam situasi tumpang tindih klaim,” menurut Aristyo, menunjukkan pengakuan implisit Indonesia terhadap klaim tersebut.
Ia menjelaskan bahwa 'joint development' mengisyaratkan pembagian sumber daya yang seharusnya berada di bawah hak berdaulat Indonesia.
"Joint development artinya kita akan sharing, kita berbagi sumber daya yang harusnya sumber daya itu milik kita," kata Aristyo.
Tetapi kesepakatan yang ada lebih mengarah pada pengakuan atas klaim China dan membuka peluang bagi negara itu untuk ikut mengelola sumber daya di wilayah yang secara hukum internasional bukan haknya.
Aristyo menduga kesepakatan ini dikeluarkan mungkin karena Indonesia ingin menarik lebih banyak investasi dari China.
Kata dia, target ekonomi yang ambisius, seperti yang dijanjikan oleh Prabowo sebesar 8 persen, mungkin mendorong kebutuhan akan investasi besar, yang dapat diharapkan dari China sebagai salah satu mitra dagang utama Indonesia.
Meskipun demikian, ia menyarankan agar Indonesia lebih berhati-hati dalam membuat kesepakatan semacam ini.
Setiap kerja sama di wilayah tersebut, tambahnya, perlu dilakukan dengan penegasan yang jelas bahwa wilayah itu adalah bagian dari Indonesia dan bahwa Indonesia tidak mengakui klaim China di sana.
Rektor Universitas Jenderal Achmad Yani sekaligus pakar hukum laut internasional, Prof. Dr. Hikmahanto Juwana, juga menegaskan pentingnya menjaga agar penguatan kerja sama antara Indonesia dan China tidak mengorbankan kedaulatan Indonesia atau merusak kepentingan bersama ASEAN di Laut China Selatan.
Ia mempertanyakan apakah klaim yang muncul dalam pernyataan bersama itu merujuk pada 'ten-dash-line' atau yang lebih dikenal dengan 'nine-dash-line' milik China, yang tumpang tindih dengan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia di perairan Natuna Utara.
Menurutnya, jika klaim tersebut diakui, akan ada perubahan mendasar dalam kebijakan Indonesia terhadap klaim wilayah China, yang berpotensi berdampak besar pada stabilitas geopolitik kawasan.
Hikmahanto meminta agar pemerintahan Prabowo tidak mengakui klaim China tersebut, mengingat hal itu bertentangan dengan undang-undang terkait wilayah nasional Indonesia.
Apalagi, Indonesia selama ini juga, tegasnya tidak pernah menyetujui perundingan terkait wilayah maritim dengan China.
Sementara itu, Peneliti SETARA Institute, Merisa Dwi Juanita, menganggap isi pernyataan bersama antara Indonesia dan China sebagai kebijakan yang keliru dan berisiko bagi Indonesia.
Menurutnya, Indonesia selama ini telah konsisten menolak klaim China di Laut China Selatan, dan adanya pengakuan baru ini membuka peluang bagi China untuk mengklaim wilayah perairan di sekitar Pulau Natuna.
Hal ini dinilai berbahaya, terutama mengingat aktivitas nelayan China yang didukung penjaga pantai mereka sering kali melanggar ZEE Indonesia di Laut Natuna Utara melalui praktik penangkapan ikan ilegal.
Lantas, Merisa mempertanyakan urgensi dari gagasan 'pengembangan bersama' di wilayah yang jelas merupakan milik Indonesia.
Baginya, menjaga hubungan diplomatik dan dagang dengan China memang penting, namun persetujuan semacam ini terlalu besar resikonya bagi kedaulatan Indonesia.
Respon Pemerintah
Pemerintah, melalui Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan (BG) memastikan, kerja sama Indonesia dengan China tidak akan berdampak pada kedaulatan Indonesia di Natuna Utara.
"Tak akan berdampak pada kedaulatan dan yurisdiksi kita terutama di Laut Natuna Utara sebagaimana yang diisukan itu," kata BG, Kamis (14/11/2024).
BG menyampaikan bahwa kerjasama tersebut telah dirancang dengan pertimbangan hukum yang matang, terutama berlandaskan UU Nomor 17 Tahun 1985, yang merupakan implementasi dari UNCLOS 1982.
Menurut dia, kerjasama ini menitikberatkan prinsip saling menghormati, kesetaraan, manfaat timbal balik, serta konsensus yang disusun sesuai aturan masing-masing negara.
kesepakatan ini, lanjutnya merupakan langkah terobosan dari Presiden Prabowo Subianto untuk meredakan ketegangan di wilayah Laut Natuna Utara.
Juga dirancang untuk menciptakan stabilitas kawasan melalui pendekatan kolaboratif, termasuk dalam bidang keamanan yang diwujudkan melalui pembentukan operasi bersama.
Pernyataan bersama Indonesia dan China yang dihasilkan dari pertemuan Prabowo dan Xi Jinping berisi 14 poin, di mana salah satu poin yang banyak mendapat sorotan adalah poin kesembilan terkait dengan kerja sama di perairan yang memiliki klaim tumpang tindih.
Dalam penjelasan tambahan, Kementerian Luar Negeri Indonesia (Kemlu) menegaskan bahwa kerja sama ini bukanlah pengakuan atas klaim “nine-dash-line” yang selama ini diperdebatkan.
Kemlu menekankan bahwa Indonesia tetap berpegang pada posisi bahwa klaim tersebut tidak memiliki dasar hukum internasional yang sah sesuai UNCLOS 1982.
Oleh karena itu, Kemlu menyatakan bahwa kesepakatan ini tidak mempengaruhi kedaulatan, hak berdaulat, atau yurisdiksi Indonesia di perairan Laut Natuna Utara.
Untuk diketahui, sengketa wilayah di Laut Natuna berawal dari klaim China yang memasukkan Laut Natuna dalam peta Sembilan Garis Putus-Putus atau Nine-Dash Line, yang pertama kali diterbitkan pada 1947.
Melalui peta ini, China mengklaim hak berdaulat atas hampir seluruh Laut China Selatan, termasuk wilayah kepulauan Paracel dan Spratly.
Namun, klaim ini bertentangan dengan aturan UNCLOS tahun 1982, yang menetapkan bahwa setiap negara berhak atas ZEE sejauh 200 mil laut dari garis pangkal pantainya.
Berdasarkan UNCLOS, Indonesia berhak mengelola Laut Natuna sebagai bagian dari ZEE-nya, karena wilayah ini berada dalam batas 200 mil laut dari garis pantai kepulauan Indonesia.
Selain China, Vietnam juga mengajukan klaim terhadap sebagian Laut Natuna, dengan alasan adanya sejarah penguasaan tradisional atas kepulauan Paracel dan Spratly.
Vietnam menganggap dirinya berhak menarik garis pangkal dari pulau-pulau yang diklaimnya, meskipun pulau-pulau tersebut sebenarnya tidak memenuhi kriteria sebagai wilayah berpenduduk permanen yang berhak atas ZEE, melainkan hanya berupa batu karang.
Sejak 2003, Indonesia dan Vietnam telah melakukan sejumlah perundingan bilateral, hingga kini sudah 12 kali, untuk mencapai kesepakatan batas ZEE di Laut Natuna, namun belum ada hasil yang final.
Sementara itu, Indonesia tidak pernah melakukan perundingan resmi dengan China terkait Laut Natuna, karena secara konsisten menolak klaim China atas Sembilan Garis Putus-Putus tersebut.
Bagi Indonesia, China hanyalah negara tetangga yang berhak melintasi wilayah Natuna tanpa melanggar kedaulatan atau hukum Indonesia.
Di tengah situasi yang rumit ini, Laut Natuna kerap menjadi titik panas yang memicu insiden, seperti pelanggaran batas, penangkapan nelayan, hingga pengejaran kapal patroli.
Pada awal 2020, perhatian dunia tertuju pada Laut Natuna ketika sekitar 50 kapal nelayan China, didampingi kapal penjaga pantai mereka, memasuki ZEE Indonesia untuk menangkap ikan secara ilegal.
Tindakan ini direspons tegas oleh Indonesia dengan mengirimkan kapal perang dan pesawat tempur untuk mengusir kapal-kapal China, bahkan Presiden Joko Widodo secara simbolis mengunjungi Pulau Natuna Besar untuk menegaskan kedaulatan Indonesia di wilayah tersebut.
Sengketa di Laut Natuna mencerminkan kompleksitas dan dinamika di kawasan Laut China Selatan, yang melibatkan berbagai negara dengan beragam kepentingan.
Penyelesaian konflik ini memerlukan kerjasama dan diplomasi konstruktif, dengan mengedepankan hukum internasional dan prinsip perdamaian.
Selain itu, peningkatan kerjasama di sektor-sektor non-politik seperti ekonomi, lingkungan, dan budaya juga diharapkan dapat menciptakan stabilitas, kedamaian, dan kemakmuran di Laut Natuna dan Laut China Selatan.
Editor: Gregorius Agung