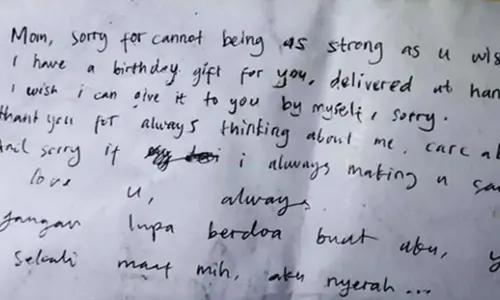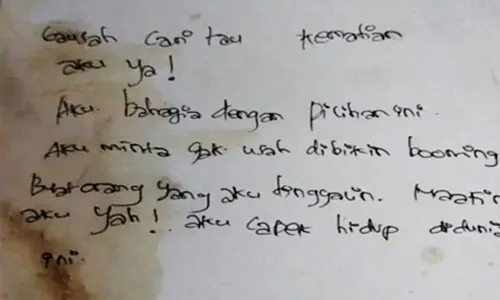PARBOABOA - Kehadiran Jepang segara membuat mutu kehidupan rakyat merosot. Keadaan kian buruk setelah Jepang mulai kelabakan menghadapi Sekutu di pelbagai palagan. Seperti dikisahkan Binsar Sitompul, bertiga dengan Gayus dan Cornel mereka pun pernah (di akhir 1944) harus menjual arang untuk menghidupi diri.
Sesuai perkembangan keadaan, rumah musik di Jalan Purbaya 21 lantas berubah menjadi markas pemuda pergerakan sejak awal 1945. Cornel pun berpaling dari dunia musik dan kian lama kian masuk ke mata pusaran gerakan politik membela kemerdekaan.
Asrul Sani berkisah (dalam tulisannya di “Gema Suasana”, 1948). Suatu hari dia bertemu Cornel. Waktu itu Cornel turun dari sebuah kendaraan dekil berlumpur karena dipakai terus-menerus. Menjawab Asrul komponis itu berucap:
“Kalau Saudara hendak mencari saya, jangan cari di rumah. Saya ada di markas API, Menteng 31. Buat sementara waktu saya meninggalkan musik. Saya sekarang merasa bebas sebebas-bebasnya dan dengan kebebasan yang saya perdapat ini saya tentu akan dapat menghalang jiwa saya. Saya tidak ingin perasaan kebebasan itu hilang. Kalau kemerdekaan kita diambil orang, ia pun akan turut hilang. Sekarang ada pertempuran untuk kebebasan ini. Saya tersangkut dalamnya.”
Tentang lagu propaganda ciptaannya ia juga menjawab Asrul Sani. Dengan membuat lagu-lagu itu, ia menyatakan, dirinya bukan lagi berkhianat tapi sudah menafikan diri sendiri. Sudah menjadi tukang pembuat lagu yang menerima order dari siapa saja. Tapi ia mengingatkan bahwa dirinya berkontribusi juga.
“Tetapi bagi saya sebetulnya ini suatu korban. Kita ini hanya perintis saja. Rakyat kita hanya mengenal toonladder [tangga nada] yang mempunyai 5 suara. Bagaimana mereka akan dapat mengerti dan menghargai lagu-lagu yang terdiri dari lebih 5 suara, apalagi simfoni-simfoni atau musik-musik klasik berat? Tetapi sekarang bagaimana? Lagu-lagu bestelan yang diperlukan Jepang untuk propaganda, yang terdiri dari suara-suara yang lengkap telah dimasukkan ke desa-desa, ke gubuk-gubuk. Lagu-lagu itu dinyanyikan di parit-parit, bekerja di kebun-kebun, oleh orang-orang yang selama ini mengenal toonladder yang bersuara 5 itu. Jangan lihat keindahan lagu itu, baik bunyi ataupun arti, tetapi lihatlah hasilnya, toonladder yang mempunyai 7 suara telah sampai ke lapisan rakyat kita yang paling bawah.
Kita tidak usah mengarang simfoni untuk sementara waktu. Schubert atau Stravinsky lama baru akan lahir di sini. Di Eropa lain halnya di sini. Waktu Beethoven lahir, ia telah mendengar Handel dan Bach, demikian berturut-turut. Jiwa itu telah lahir bersamanya ke dunia. Kita di sini tidak. Saya baru kenal Beethoven waktu saya hampir dewasa. Semuanya barang usang yang masih baru bagi kita. Yang pertama-tama dapat kita lakukan ialah memasukkan kesanggupan menangkap perasaan musik ke dalam dada rakyat kita. Menurut saya dalam hal ini ada juga sumbangan saya.”
Persuaan itu yang terakhir bagi keduanya. Cornel kemudian ikut bertempur di Tanah Tinggi, Senen dan Kramat. Pahanya pun kena tembak; jalan dia mendekam di Pakem, tempat yang kala itu identik dengan dua jenis insan malang: penderita TBC dan orang gila.
Tembang Puitik
Masa 1943-1945 merupakan puncak kreativitas Cornel, orang yang menurut Asrul Sani, “tidak pernah menganggap hidup ini sebagai main-main dan selalu mencari hal-hal yang tersembunyi di balik sesuatu benda atau kejadian”. Selain sejumlah karya yang telah disebut, waktu itu ia juga menghasilkan “O, Ale Alogo” dan “Andigan Ma”.
Cornel pernah mengatakan bahwa lagu yang baik adalah yang syair dan melodinya bersenyawa. Persenyawaan harus sampai pada detilnya, seperti alunan dan tekanan antara kata dan melodi. Syair dan melodinya harus saling mengisi dan mendukung dalam mencapai klimaks atau anti-klimaks. Masalahnya, dalam konteks Indonesia hal seperti itu tak mudah dibuat.
Dalam artikel di majalah Arena yang ia tulis setibanya di Yogya tahun 1946, dia menyebut tekanan bahasa Indonesia berbeda bahkan bertentangan dengan sifat tekanan musik. Kata Indonesia umumnya mempunya tekanan pada suku kedua dari belakang (kecuali suku kedua dari belakang tersebut terdapat e pepet sehingga tekanan kata otomatis berpindah ke suku terakhir. Sedangkan tekanan kalimat lagu biasanya terletak pada nada akhir). Bagaimana hal ini bisa diatasi?
Untuk mengatasi masalah ini atau memperlembek pertentangan, menurut Liberty Manik, Cornel menawarkan dua jalan keluar. Pertama, menyusun teks buat lagu dengan mengusahakan agar untuk suku kedua dari akhir kata dicarikan e pepet. Seperti dalam “Maju Tak Gentar.” Kedua, menggandai nada terakhir suatu kalimat lagu sehingga nada terakhir tersebut menimbulkan sebuah syncope (hilangnya bunyi atau huruf di tengah kata). Cornel, kata Liberty, melakukan kedua cara itu dalam karyanya. Alhasil keganjilan nada praktis tak terasa. Seperti “O, Angin” dan “Kemuning”.
“O, Angin” dan “Kemuning’ merupakan karya yang paling dipuji Liberty Manik. Doktor musik lulusan Jerman ini menyebutnya sebagai dua lagu seni (kunstlied) dalam arti yang sebenarnya, yang merupakan permata berharga bagi perbendaharaan lagu-lagu seni Indonesia. “Baik melodi maupun akkor dari iringan pianonya nampaknya seluruh diabdikan pada keindahan gerak dan tekanan kata. Jarang kita menjumpai lagu Indonesia dimana melodi dan syair berpadu sebegitu organis,” ucap pencipta “Satu Nusa Satu Bangsa”.
‘O, Angin’
O, angin, bawa keluhku,
bersama kau, melalui pegunungan hijau
kepada ’dinda yang amat tercinta
Bawa keluhku bersama kau
O, angin, bawa cintaku,
kepada dara tercinta tidak ketara,
kepada m’lati, si jantung hati.
“Bawa cintaku kepada dara” Karya Cornel Simanjutak, menurut penyanyi sopran Indonesia terkemuka saat ini, Binu D. Sukaman, merupakan repertoar standar yang perlu diketahui, dipelajari dan dinyanyikan setiap penyanyi tembang puitik atau seriosa Indonesia. Dalam beberapa kurikulum sekolah musik, ciptaan Cornel termasuk repertoar yang diharuskan.
Karya-karya itu mulai dari yang bersifat sederhana, melodius, cantik, dengan harmoni yang mudah dinikmati, dan penggunaan syair yang mudah dicerna—seperti "Mari Berdendang" dan "Mekar Melati"—hingga lagu-lagu yang mempunyai harmoni yang lebih kompleks dan tingkat penguasaan yang lebih sulit seperti "Kemuning" dan "O Angin" dan "Wijaya Kusuma", yang didasarkan pada puisi Sanusi Pane. “Lagu "O Angin" dan "Kemuning" itu indah.
Tapi, untuk membawakannya dituntut teknik menyanyi yang sulit karena melodi-melodi panjang dan interval-interval antar not yang mengharuskan penguasaan pernapasan dan pelafalan yang khusus juga. Di samping pendalamam syair yang mengharuskan penyanyi membaca serta menyanyikan apa yang tertera di antara jalinan kata dan melodi; to read between the lines,” papar Binu.
‘Kemuning’
Kemuning, waktu dahulu aku menanti di bawah daunmu
dan aku selalu melihat adinda mendapatkan daku
Kami membisikkan cinta berganti-ganti.
Sekarang aku menanti sudah lama, sesudah bertahun tiada bersua:
Tidak datang seorang pun jua.
Kemuning, dimana gerangan adinda utama
Lagu-lagu Cornel, menurut pengamatan Binu, telah menjadi lagu standar pada setiap kompetisi vokal. “Itu yang saya amati di setiap acara Bintang Radio dan Televisi. Itu semua karena Cornel Simanjuntak merupakan tokoh penting dalam musik vokal di Indonesia, khususnya jenis musik seriosa atau tembang puitik.”
Penulis Hersri Setiawan dalam artikelnya bertahun 1982 menyebut Cornel tokoh terkemuka Angkatan ’45 di bidang musik, estetik maupun artistik. Pelopor dan peletak dasar bagi musik Indonesia baru, yang terobosannya jadi model bagi komponis lain. Dia di bidang musik, menurut Hersri, sama dengan Chairil Anwar di bidang sastra.
Sebelum terobosan Cornel, menurut penulis yang lama tinggal di Eropa ini, masyarakat kita praktis hanya mengenal lagu keroncong, stambul, atau langgam. Sehingga tak heran kalau lagu “Indonesia Raya” yang dinyanyikan massa dalam rapat akbar di lapangan Ikada, Jakarta, pada 19 Agustus 1945, terdengar dalam berbagai cengkok. Hersri menulis:
“Lalu apa yang dilakukan Cornel lebih lanjut? Pada dua hal, massa dan musik. Pada massa, ia memelek-nadakan rakyat Indonesia dengan sekaligus memberikan dasar pendidikan musik secara praktis. Cara yang ditempuh ialah dengan menggubah lagu-lagu mars yang umumnya sederhana dan mudah, dengan bahasa Indonesia yang baik namun mempunyai daya agitatif, padat tapi juga orisinal.”
Cornel Simanjutak meninggal sekitar 78 tahun silam. Pada 1957, tepat 11 tahun setelah ia berpulang, sebuah konser digelar untuk memperingati dia. Dipimpin Nortier Simanungkalit, paduan suara beranggota 500 pelajar dan mahasiswa membawakan karya-karyanya. Mereka diiringi 70 musisi yang dipimpin Nicolai S. Varfolomeyeff. Waktu itu, menurut Hersri, makam anak Siantar ini di Kerkop juga diperbaiki.
Pada 1978 sang komponis yang menerima Satya Lencana Kebudayaan secara anumerta (1962) ini kembali mendapat perhatian: dengan upacara resmi jenazahnya dipindahkan ke Taman Makam Pahlawan Kusumanegara, Semaki, Yogya. Kini, setelah hampir 78 tahun lampau, nama sang seniman-pejuang sesekali masih disebut orang. Selain dalam konteks ciptaannya, juga untuk merujuk tempat tertentu. Di antaranya sebuah ruas jalan di Yogyakarta yang menghubungkan Pakem dengan Terban yang tak jauh dari kampus UGM Bulaksumur, dan sebuah taman di Jakarta. Ya, untung juga namanya telah diabadikan untuk tempat tertentu sehingga masih lumayan acap disebut.
Editor: Rin Hindrayati