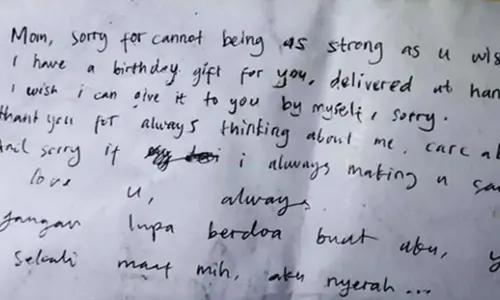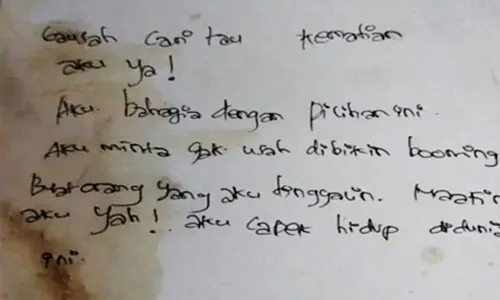PARBOABOA - Meiliana Yumi (42) menceritakan ihwal tanah adat Rakyat Penunggu Kampong Menteng Tualang Pusu dengan berapi-api. Suatu sore di penghujung Februari lalu itu, udara sedang cerah-cerahnya di Desa Amplas, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kota Medan.
Sesekali angin sejuk berembus. Yumi menjamu Parboaboa dengan segelas jeruk kasturi di kediamannya. Dari teras tempat kami berbincang, tampak sebidang lahan yang belum digarap.
Sejauh mata memandang di kawasan tanah adat itu, rumah tersebar jarang-jarang. Pemandangan lebih didominasi lahan bercocok tanam masyarakat.
Mata Yumi tampak berkaca-kaca ketika obrolan menyinggung nasib tanah adat ke depan. Pada 2020, masyarakat adat mendapat surat dari PT Perkebunan Nusantara (PN) II.
Isinya mengabarkan bahwa wilayah yang mereka tempati akan masuk dalam megaproyek Kota Deli Megapolitan. Sebagian pembangunan kota satelit tersebut sudah mulai berjalan meski areanya masih jauh dari Menteng Tualang Pusu.
'Rakyat Penunggu' Kampong Menteng Tualang Pusu tidak tahu pasti kapan proyek itu akan mulai menjamah lahan mereka. "Sampai sekarang, inilah yang menghantui kami," kata Yumi yang merupakan sekretaris Lembaga Adat Rakyat Penunggu Kampong Menteng Tualang Pusu.
'Rakyat Penunggu' merupakan sebutan bagi masyarakat adat yang menempati kawasan di Kabupaten Langkat dan Kabupaten Deli Serdang, Sumatra Utara. ‘Rakyat Penunggu’ tersebar di 76 kampung.
Kelompok masyarakat adat Kampong Menteng Tualang Pusu salah satu di antaranya. Mereka, berdasarkan penuturan Yumi, sebenarnya sudah mulai mendengar desas-desus rencana Kota Deli Megapolitan sejak 2017.
Proyek kota mandiri tersebut merupakan hasil kongsi antara PTPN II dengan raksasa pengembang Grup Ciputra. Dicanangkan sejak 2011, Deli Megapolitan disebut-sebut menyedot dana Rp 128 triliun.
Pembangunannya akan meliputi luasan tanah 8.077,73 hektare. Nah, 357 hektare tanah yang diklaim masyarakat adat Kampong Menteng Tualang Pusu masuk dalam rencana proyek itu.
Pembangunan proyek dikhawatirkan akan kembali memantik konflik perebutan tanah antara perusahaan dan masyarakat adat yang telah berlangsung lama. Sengketa masyarakat adat dan PTPN bermula ketika pemerintah menerbitkan Undang-Undang Pokok Agraria tahun 1960.
Beleid tersebut menerapkan sistem Hak Guna Usaha (HGU) bagi usaha perkebunan. Penguasaan tanah adat jatuh ke PTPN II, yang dulu masih bernama PTPN IX, sebagai pemegang HGU.
Sejak itu, sengketa lahan tak terhindarkan. Sebab, hingga kini pun, PTPN selalu mendasarkan alas hak mereka atas tanah adat kepada HGU yang diberikan pemerintah.
Eskalasi konflik paling keras terjadi memasuki periode 2000-an. Tahun 2003, masyarakat adat berusaha merebut kembali lahan mereka. "Karena saat itulah baru tercium bahwa kontrak dari HGU lahan itu sebenarnya sudah selesai," ujar Yumi.
Setelah itu, masyarakat adat dan PTPN beberapa kali terlibat bentrokan. Pada 2010-an, masyarakat adat mengambil alih lahan yang diyakini milik mereka. Kawasan Kampong Menteng Tualang Pusu, berdasarkan data Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA), telah didaftarkan sebagai tanah adat sejak 22 April 2012.
BRWA telah menyertifikasi wilayah ulayat tersebut. Namun, dari 357 hektar total lahan adat 'Rakyat Penunggu' Kampong Menteng Tualang Pusu, menurut Yumi, baru 97,8 hektare yang dikuasai masyarakat adat. Kini, terdapat 378 kepala keluarga dengan 700-an jiwa masyarakat adat yang menempati lokasi itu.
Pihak PTPN II belum memberikan konfirmasi terkait tumpang tindih klaim alas hak di lahan adat tersebut. Parboaboa sudah menghubungi Kasubbag Humas PTPN II, Rahmat Kurniawan, dan melayangkan surat permohonan wawancara pada 25 Maret 2024. Namun, pihak PTPN II belum memberikan tanggapan hingga berita ini ditayangkan.
Jalan Terjal Memperjuangkan Pengakuan
Upaya masyarakat adat Kampong Menteng Tualang Pusu sebenarnya mendapat momentum pada 2020. Pemerintah Desa Amplas memberi mereka SK Pengakuan Keberadaan Masyarakat Adat Rakyat Penunggu.
Namun, di tahun yang sama masyarakat adat justru mendapat kabar pembangunan Kota Deli Megapolitan. Yumi mengatakan, lembaga adatnya kini menargetkan mendapat legalitas pengakuan berupa sertifikat kepemilikan komunal dari Kementerian ATR/BPN.
"Kalau misalkan keluar suratnya, harapannya kita sudah tidak diganggu lagi,” tegas Yumi.
Sertifikat komunal ini nantinya bisa memberi kepastian hukum atas penguasaan tanah adat. Karena bersifat kolektif, tanah dengan sertifikat semacam ini tidak bisa diperjualbelikan.
Namun, upaya ke arah sana mendapat tantangan dari internal masyarakat adat. Mereka kini terbelah.
Ada kelompok yang bersedia digusur dari tanah adat sepanjang mendapat ganti rugi yang sesuai. Kelompok lain ingin mempertahankan tanah adat tapi dengan sertifikat individu.
Yumi menduga ada pihak yang sengaja memecah belah kekuatan masyarakat adat Menteng Tualang Pusu. Sinyalemen itu juga diendus oleh Ansyurdin, Ketua Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Wilayah Sumatra Utara.
Masalah masyarakat adat dalam mempertahankan tanah ulayat kian pelik. Pasalnya, belum ada kebijakan politik yang berpihak kepada mereka.
Ansyurdin menjelaskan, legalitas tanah bagi masyarakat adat tak bisa diterbitkan tanpa peraturan daerah yang memberi perlindungan hak adat. "Tidak bisa juga dibuat sertifikat komunal kalau tidak ada payung hukumnya," ia berujar.
Sementara proses penggodokan perda mandek di DPRD Provinsi Sumatra Utara. AMAN sudah berupaya mendorong pengesahannya sejak 2015 lalu.
Sembilan tahun berselang tak junjung ada titik terang. Padahal, perda perlindungan hak adat masuk dalam program legislasi daerah (Prolegda) tingkat provinsi. Pembahasannya kini masih jalan di tempat.
Di tingkat nasional, juga belum ada produk legislasi yang berpihak pada masyarakat adat. Ansyurdin menyebut undang-undang yang membahas khusus masyarakat adat tak kunjung rampung.
Proses inisiatifnya bahkan sudah dimulai sejak 2009. Padahal, konstitusi sejatinya mengakui eksistensi masyarakat adat.
Mengacu pada UU Dasar 1945, Pasal 18 B ayat (2), negara mengakui dan menghormati masyarakat adat sebagai suatu entitas. Pasal 28 I ayat (3) juga menyebutkan kewajiban negara menghormati keberadaan dan hak masyarakat adat.
Komitmen politik negara dipertanyakan untuk mengurai konflik lahan masyarakat adat. "Kalau memang pemerintah serius tolong undang-undang ini diterbitkan, kalau tidak konflik terus terjadi," ungkap Ansyurdin.
Irham Buana, Wakil Ketua DPRD Sumut, mengeklaim lembaganya sudah mengambil inisiatif Perda mengenai pengakuan masyarakat adat dan hak ulayat sejak tahun dua tahun lalu. Aspirasi itu masuk lewat Komisi A DPRD.
Beberapa kali DPRD Sumut menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama pemangku kepentingan. Kelompok masyarakat adat juga diundang ke DPRD Sumut dalam rangka pembahasan raperda.
"Itu sudah dilakukan bahkan sudah melalui kajian akademisnya juga sudah," ungkap Irham saat diwawancarai PARBOBOA melalui sambungan telepon, Minggu (24/03/2024).
Politisi asal Partai Golkar ini menepis anggapan bahwa pemerintah lamban. Menurutnya, pengesahan Perda untuk melindungi masyarakat adat tetap menjadi agenda prioritas.
Kendalanya, kata dia, terletak pada masih adanya perbedaan persepsi menyangkut masyarakat adat dan hak ulayat. Selain itu, DPRD juga perlu mempertimbangkan efek sosial yang mungkin timbul.
Ia mengungkapkan, ada kekhawatiran kehadiran perda justru memicu persoalan sosial yang berujung pada konflik horizontal. "Ini yang harus kita cermati dengan sungguh-sungguh, jangan sampai kemudian justru korbannya adalah masyarakat adat sendiri," ucap Irham.
Ia menggarisbawahi kemungkinan perda malah dimanfaatkan kelompok-kelompok yang tidak termasuk dalam bagian masyarakat adat.
Reporter: Ghiyatuddin Yauzar
Editor: Andy Tandang