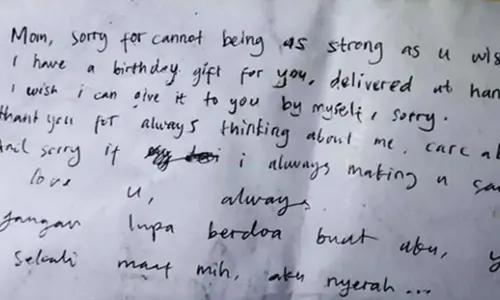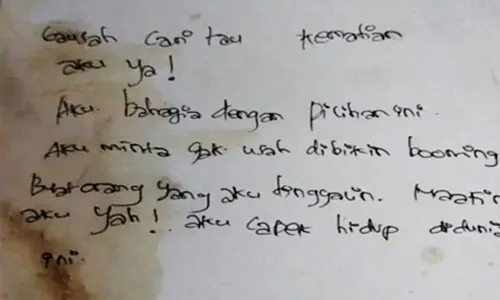PARBOABOA, Jakarta - 13 November 2024 adalah momen bersejarah yang menandai 26 tahunnya tragedi kemanusiaan semanggi I.
Namun, dalam rentang waktu yang panjang itu, negara tak kunjung mengadili pelaku penembakan yang menewaskan beberapa orang mahasiswa.
Itulah sebabnya organisasi masyarakat sipil Amnesty International mengultimatum pemerintah berhutang untuk menghormati serta menegakkan HAM.
Peristiwa ini merupakan ironi reformasi, kata Amnesty, karena dilakukan persis pada hari ketika MPR mengesahkan TAP MPR No. XVII/MPR/1998 Tentang HAM, tepatnya pada 13 November 1998.
Tak hanya itu, menurut mereka Tragedi Semanggi I merupakan kejahatan yang paling jelas bukti-buktinya; dimana peluru yang ditembakkan jelas berasal dari senjata apa; begitu pula pasukan yang ada di lokasi jelas berasal dari mana.
Direktur Amnesty International, Usman Hamid menyayangkan tidak adanya niat baik dari negara untuk menuntut dan mengadili pelaku lapangan dan komandonya.
Padahal kata dia, insiden puluhan tahun silam itu bukan sekedar sejarah belasan jiwa mahasiswa dan warga sipil biasa yang melayang akibat peluru tajam aparat, tetapi juga mengingatkan perjuangan mahasiswa pada era reformasi.
"Dari mulai mengadili mantan presiden Soeharto, membatasi kekuasaan presiden, hingga menghapuskan dwifungsi militer," kata Usman belum lama ini.
Hari-hari ini, agenda reformasi itu, tegasnya, justru diinjak-injak oleh perilaku sejumlah elite politik, hal yang disesali oleh para orang tua korban, tetapi terus berjuang "melalui Aksi Kamisan."
Aksi Kamisan adalah sebuah gerakan damai yang diadakan setiap hari Kamis di depan Istana Negara, dipelopori oleh para korban dan keluarga korban pelanggaran HAM di Indonesia.
Aksi ini pertama kali dilaksanakan pada 18 Januari 2007 sebagai bentuk tuntutan kepada negara untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM berat.
Adapun peristiwa-peristiwa yang menjadi sorotan adalah Tragedi Semanggi, Tragedi Trisakti, kerusuhan 13-15 Mei 1998, Peristiwa Tanjung Priok, Peristiwa Talangsari 1989, dan masih banyak lagi.
Aksi tersebut berawal dari inisiatif tiga keluarga korban pelanggaran HAM berat, yaitu Maria Catarina Sumarsih, ibu dari Bernardus Realino Norma Irmawan, mahasiswa yang gugur dalam Peristiwa Semanggi I; Suciwati, istri dari almarhum aktivis HAM Munir Said Thalib; serta Bedjo Untung, perwakilan keluarga korban penahanan dan pembunuhan massal terhadap orang-orang yang dicap terkait PKI pada periode 1965-1966.
Aksi Kamisan menjadi simbol keteguhan perjuangan menuntut keadilan dan menyuarakan hak-hak yang dirampas, serta menjadi pengingat bagi bangsa tentang pentingnya penegakan HAM di Indonesia.
Usman berkata, pada 11 Januari 2023, Presiden Joko Widodo sebenarnya telah mengumumkan pengakuan resmi atas 12 kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu, termasuk Tragedi Semanggi I dan II.
Pengumuman ini awalnya diharapkan menjadi langkah awal dalam menyelesaikan berbagai kasus pelanggaran HAM berat di Indonesia, namun sayangnya, belum diikuti oleh tindakan konkret dari pihak berwenang.
"Pengakuan tanpa upaya penegakan hukum hanyalah retorika kosong," kata Usman sembari menegaskan Jaksa Agung memiliki tanggung jawab legal dan moral untuk mengusut pelaku dan menghadirkan keadilan bagi korban.
Ketiadaan langkah tegas ini, sebutnya, "menunjukkan kegagalan negara dalam menegakkan hak asasi manusia yang menjadi amanat Reformasi 1998."
Ia juga menegaskan, salah satu pencapaian penting dari era reformasi adalah terbentuknya Pengadilan HAM, yang didirikan melalui Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000.
Kehadiran pengadilan ini semestinya menjadi harapan baru bagi korban pelanggaran HAM berat untuk mendapatkan keadilan, termasuk bagi mereka yang terdampak dalam Tragedi Semanggi I.
Namun, lebih dari dua dekade setelah undang-undang tersebut disahkan, keadilan yang diharapkan masih jauh dari kenyataan. Pengadilan HAM, yang merupakan simbol dari upaya reformasi hukum, belum menunjukkan keberpihakan dalam mengusut kasus-kasus besar tersebut.
Usman mengingatkan, negara melalui berbagai otoritas, termasuk pemerintah, aparat hukum, dan Komnas HAM, seharusnya menjalankan mandat yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000.
Penegakan hukum yang konsisten dan tegas terhadap pelanggaran HAM berat, kata dia, adalah bukti penghargaan atas perjuangan para korban dan keluarga mereka yang hingga kini masih menanti kepastian keadilan.
Tragedi Semanggi I terjadi pada 13 November 1998, di sekitar kampus Universitas Atmajaya dan persimpangan Semanggi, Jakarta.
Peristiwa ini muncul di tengah kuatnya gelombang demonstrasi mahasiswa dan masyarakat yang menolak pengaruh tokoh-tokoh Orde Baru yang masih berkuasa. Mereka menuntut reformasi, termasuk pengadilan bagi tokoh-tokoh lama, pembatasan masa jabatan presiden, dan penghapusan dwifungsi ABRI (sekarang TNI).
Demonstrasi tersebut direspons dengan tindakan represif oleh aparat keamanan yang menggunakan kekuatan berlebihan, mengakibatkan kekerasan dan pembunuhan di luar hukum.
Berdasarkan laporan media dan Tim Relawan untuk Kemanusiaan, dalam Tragedi Semanggi I tercatat 17 warga sipil tewas dan 456 lainnya luka-luka.
Setahun setelahnya, Tragedi Semanggi II meletus, tepatnya pada 24 September 1999, menyebabkan 11 warga sipil tewas dan 217 lainnya terluka.
Meski ada upaya pengadilan terhadap sejumlah anggota kepolisian dan tentara terkait penembakan ini, proses tersebut dinilai gagal memberikan keadilan bagi korban dan mengungkap pihak yang bertanggung jawab.
Keluarga korban terus menuntut agar Tragedi Semanggi I dan II diadili melalui mekanisme Pengadilan HAM, namun upaya ini belum membuahkan hasil.
DPR, melalui veto Badan Musyawarah DPR pada Maret 2007, dan pernyataan Jaksa Agung ST Burhanuddin pada rapat kerja dengan Komisi III DPR pada 2020, berpendapat bahwa tragedi tersebut tidak termasuk pelanggaran HAM berat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.
Keluarga korban menggugat pernyataan Jaksa Agung tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta, dan pada Desember 2020 PTUN menyatakan bahwa Jaksa Agung bersalah. Namun, Jaksa Agung mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) yang akhirnya membatalkan putusan PTUN Jakarta.
Keluarga korban kemudian mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA), tetapi pada 2 September 2021, MA menolak permohonan kasasi tersebut.
Editor: Gregorius Agung