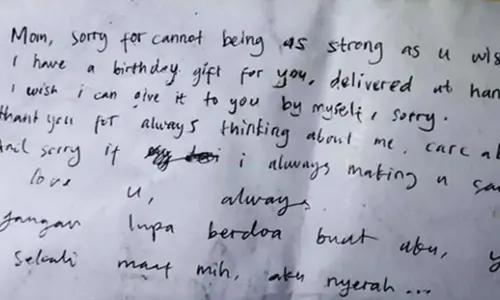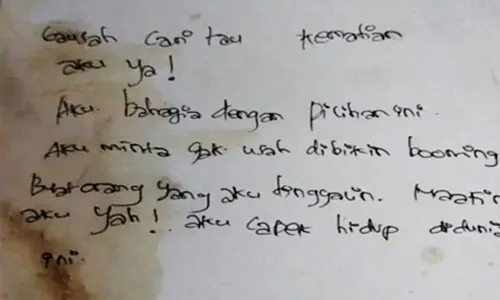PARBOABOA, Jakarta - Demonstrasi menjadi salah satu bentuk ekspresi yang sah dalam sistem demokrasi guna menyampaikan aspirasi atau pendapat.
Gerakan yang menghadirkan ratusan bahkan ribuan massa tersebut dinilai sebagai instrumen penting dalam menuntut kebijakan dan hak-hak rakyat yang terkooptasi kepentingan penguasa.
Sejarah menunjukkan, aksi massa yang memprotes kebijakan pemerintah berdaya memberi pengaruh signifikan pada perubahan kebijakan, bahkan menurunkan kekuasaan.
Salah satu peristiwa demonstrasi penting di Indonesia pernah dilakukan para mahasiswa untuk melengserkan kekuasaan mantan presiden Soeharto pada Mei 1998.
Gerombolan massa akhirnya berhasil menduduki kantor DPR/MPR dan mengusik Soeharto untuk mundur dari jabatannya. Tepat pada 21 Mei 1998, otoritas Soeharto pun lengser.
Publik Indonesia mengenal peristiwa bersejarah tersebut dengan sebutan Tragedi 1998 di mana kekuasaan Soeharto selama 32 tahun akhirnya berhasil ditumbangkan.
Praktik demonstrasi serupa terus digunakan untuk menyuarakan aspirasi masyarakat. Sistem demokrasi di Indonesia mengakomodasi adanya dinamika demonstrasi dengan batasan-batasan tertentu.
Namun, belakangan muncul fenomena yang merusak nilai demonstrasi, yakni dengan adanya demonstrasi bayaran.
Fenomena ini tidak hanya merusak citra demokrasi, tetapi juga menimbulkan berbagai persoalan etika dan kepercayaan publik.
Demonstrasi bayaran adalah aksi massa yang diorganisasi bukan karena dorongan murni dari para peserta untuk menyuarakan aspirasi, melainkan karena adanya imbalan uang atau fasilitas lain.
Para peserta umumnya tidak memahami isu yang mereka perjuangkan karena diundang melalui jaringan tertentu untuk ikut serta.
Imbalan tersebut biasanya diberikan dalam bentuk uang transportasi, konsumsi, atau bahkan uang tunai yang langsung diterima pelaku demonstrasi.
Liputan khusus PARBOABOA pada Senin (18/11/2024) membenarkan maraknya praktik demonstrasi bayaran. Aksi ini ditengarai melibatkan berbagai kelompok dan aktor dengan motif politik maupun ekonomi.
Demonstrasi yang dilakukan di kantor Indonesia Corruption Watch (ICW) beberapa waktu lalu menguatkan hal serupa. Para demonstran ditunggangi pihak tertentu dengan skenario yang sudah diatur.
Dalam wawancara yang dilakukan dengan sejumlah narasumber, diketahui bahwa praktik serupa melibatkan penyedia jasa mobilisasi yang bertujuan menghadirkan dan menggerakkan massa bayaran.
Harga untuk setiap case berbeda. Indra, bukan nama sebenarnya, yang kerap menerima orderan untuk menggerakkan massa mematok harga Rp100 ribu per kepala.
Sebagai koordinator lapangan (korlap), ia akan menerima bayaran sebesar Rp500 ribu. Semakin besar jumlah massa yang diperlukan, semakin banyak pula korlap yang dilibatkan dalam aksi tersebut.
"Biasanya, satu korlap hanya mampu mengumpulkan sekitar 100 orang," ujarnya.
Ia melanjutkan, pemesan juga harus menyiapkan anggaran untuk biaya transportasi massa. Korlap biasanya menyewa bus Kopaja dengan kapasitas 30 orang per unit.
Jumlah bus yang digunakan akan disesuaikan dengan banyaknya massa yang dikerahkan untuk melakukan demonstrasi.
"Untuk satu lokasi demonstrasi, biaya sewa bus mencapai Rp600 ribu per unit. Jika ada tambahan lokasi aksi, biayanya naik Rp50 ribu per titik," jelasnya.
Secara umum, praktik demonstrasi bayaran memiliki tiga lapisan aktor. Lapisan pertama melibatkan pemilik dana atau pihak yang memiliki kepentingan khusus.
Mereka kemudian mempercayakan tugas ini kepada seseorang, yaitu senior dari kalangan mahasiswa yang aktif dalam organisasi tertentu untuk mengorganisasi massa.
Selanjutnya, lapisan kedua terdiri dari para senior. Mereka bertugas merekrut mahasiswa lainnya untuk menjadi peserta aksi demo sekaligus menyiapkan koordinator lapangan (korlap).
Kelompok korlap inilah yang menjadi lapisan ketiga dalam hierarki pengorganisasian. Mereka membawahi para demonstran yang diambil dari berbagai kalangan.
Sebuah Anomali
Fenomena demonstrasi bayaran memiliki dampak negatif bagi keberlangsungan sistem demokrasi di Indonesia.
Demonstrasi yang semestinya menjadi medium aspirasi rakyat berubah menjadi alat manipulasi. Hal ini merusak kredibilitas aksi massa di mata publik dan melemahkan nilai demokrasi yang murni.
Fenomena serupa juga menjadi bagian dari eksploitasi masyarakat. Peserta aksi sering kali hanya dimanfaatkan tanpa memahami risiko atau dampak yang mereka hadapi.
Dalam beberapa kasus, mereka berpotensi mengalami bentrok atau kriminalisasi hingga berujung pada urusan dengan pihak keamanan.
Organisasi masyarakat sipil Publish What You Pay (PWYP) Indonesia turut mengkritisi praktik demokrasi di Indonesia, khususnya terkait keberadaan massa bayaran.
Direktur PWYP Indonesia, Maryati Abdullah, menyatakan bahwa praktik semacam ini mencerminkan kondisi demokrasi yang memprihatinkan.
Ia menyoroti demonstrasi pro-revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (RUU KPK), di mana banyak peserta aksi tidak memahami inti permasalahan yang mereka suarakan.
"Menurut saya, itu adalah anomali. Kebebasan warga negara dan suara mereka terhalangi oleh praktik bayaran, yang menciptakan demokrasi yang tidak sehat," ujar Maryati pada 2019 lalu.
Maryati menegaskan, massa bayaran tidak hanya merusak demokrasi, tetapi juga menghambat kebebasan warga negara untuk menyampaikan pendapat secara bebas.
Ia menyebut kondisi ini sebagai ironi demokrasi Indonesia, di mana kelompok-kelompok ekonomi lemah dimanfaatkan demi kepentingan pihak tertentu.
"Dengan cara seperti itu, mereka yang berasal dari kalangan ekonomi menengah ke bawah menjadi sasaran mobilisasi untuk tujuan yang tidak mencerminkan demokrasi substantif," jelasnya.
Selain itu, Maryati mengungkapkan bahwa kualitas demokrasi di Indonesia pasca reformasi justru menurun.
Ia mengidentifikasi tiga indikator utama penurunan tersebut, antara lain proses legislasi di parlemen yang terburu-buru, terutama dalam revisi undang-undang.
Selain itu, minimnya partisipasi publik dalam penyusunan kebijakan dan rendahnya transparansi dan akuntabilitas dalam proses legislasi menjadi faktor penyebab lain.
"Situasi demokrasi substantif saat ini sangat menantang. Bahkan, ada indikasi penurunan kualitas demokrasi," tambahnya.
Namun demikian, ia mengakui bahwa Indonesia memiliki landasan kuat untuk keterbukaan informasi publik melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. Meski demikian, implementasi transparansi masih menjadi tantangan besar.
"Parlemen kita sudah dianggap sebagai open parliament di tingkat global, tetapi dalam praktiknya, keterbukaan data dan proses pembahasan legislasi masih jauh dari progresif," pungkasnya.
Persoalan tersebut tentu perlu diatasi segera. Pemerintah dan organisasi masyarakat sipil perlu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya aspirasi yang murni.
Edukasi ini juga harus menyentuh isu-isu sosial dan politik agar masyarakat tidak mudah terpengaruh iming-iming imbalan.
Di pihak lain, transparansi penyelenggaraan demonstrasi harus dibuat. Perlu ada regulasi yang mewajibkan penyelenggara aksi massa untuk melaporkan tujuan dengan transparan.
Aparat hukum juga dituntut tegas dalam menindak pelaku yang memanfaatkan demonstrasi sebagai alat manipulasi. Langkah ini mencakup investigasi terhadap sponsor atau dalang di balik demonstrasi bayaran.
Singkatnya, langkah nyata dari pemerintah, aparat hukum, dan masyarakat luas sangat diperlukan untuk menjaga kemurnian aspirasi rakyat.
Dengan mengatasi akar masalahnya, Indonesia dapat kembali menjadikan demonstrasi sebagai simbol kekuatan rakyat yang sesungguhnya, bukan sekadar alat manipulasi pihak tertentu.
Editor: Defri Ngo